Home » All posts
Karakteristik Sistem Pendidikan Terbaik Finlandia
*tulisan ini merupakan saduran.
Finlandia adalah negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Berdasarkan survei Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2000 dengan membandingkan pelajar usia 15 tahun dari berbagai negara, Finlandia meraih peringkat teratas. Survei itu membandingkan pelajar usia 15 tahun dari berbagai negara pada bidang baca-tulis, matematika, dan sains.
Survei yang dilakukan setiap 3 tahun sekali oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2009 menempatkan pelajar Finlandia tetap nyaris teratas pada ketiga kompetensi tersebut. Sementara itu survei global mengenai kualitas hidup oleh Newsweek, Finlandia ditasbihkan sebagai negara dengan kualitas hidup nomor satu di dunia.
Pasi Sahlberg, Direktur Mobilitas Internasional, Departemen Pendidikan Nasional Finlandia telah menulis buku tentang kesuksesan sistem pendidikan Finlandia yang berjudul Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?. Berikut adalah karakteristik sistem pendidikan Finlandia yang terbaik di dunia.
Pilihan Sekolah Sedikit dan Semua Dikelola Pemerintah
Mulai sekolah setingkat TK sampai perguruan tinggi, pelajar-pelajar Finlandia bersekolah di sekolah negeri. Hanya ada sedikit sekolah swasta di Finlandia, dan bahkan semuanya dibiayai pemerintah. Tidak ada yang diperbolehkan untuk membebankan biaya sekolah.
Variasi pilihan sekolah di Finlandia sangat sedikit. Di sana, pilihan sekolah tidak lagi menjadi prioritas utama. Kunci kesuksesan Finlandia dalam memperbaiki sistem pendidikannya adalah mereka tidak mengejar keunggulan akademis (excellence), tapi kesetaraan (equity).
Setiap anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tanpa melihat latar belakang keluarga, pendapatan, atau lokasi geografis. Pendidikan utamanya bukanlah cara untuk menghasilkan individu yang cerdas, tetapi sebagai alat untuk meratakan kesenjangan sosial. Keunggulan akademis bukanlah prioritas khusus bagi Finlandia, tetapi Finlandia berhasil menciptakan keunggulan akademik melalui fokus kebijakan pada kesetaraan.
Finlandia menyediakan sekolah yang sehat dan lingkungan yang aman untuk anak-anak. Mereka menawarkan semua anak makanan sekolah gratis, akses mudah ke perawatan kesehatan, konseling psikologis, dan bimbingan individual.
Tidak Ada Kompetisi di Sekolah Finlandia
Sistem pendidikan Finlandia juga tidak mengenal istilah kompetisi dan sistem peringkat. Tidak ada daftar sekolah terbaik atau guru terbaik di Finlandia. Pendorong utama dari kebijakan pendidikan bukanlah persaingan antar guru dan antar sekolah, tapi kerjasama. Siswa dengan development disorder ataupun penyandang cacat diletakkan pada kelas yang sama dengan siswa umum lainnya. Mereka tidak mengukur prestasi hanya untuk memberi label pada siswa.
Finlandia memandang kompetisi dalam lingkungan pendidikan merupakan konsep yang destruktif. Mental anak dapat dihancurkan oleh evaluasi terus-menerus dan membuat anak-anak kurang percaya diri dengan kemampuannya. Bagi Finlandia, ketika anak-anak dapat unggul pada apa yang mereka dapat lakukan dengan baik, bukan diukur untuk memenuhi standar, mereka dapat menghasilkan performa yang terbaik.
Anak-anak harus diberikan pendidikan sehingga mereka dapat berkembang terlepas dari bakat mereka. Tujuan pendidikan seyogianya dapat membentuk anak menjadi manusia yang lebih baik yang menghargai diri mereka sendiri dan dapat bersosialisasi dalam kehidupan tanpa berpikir bahwa mereka lebih 'pintar' atau sebaliknya, tidak berharga.
Tidak Ada Ujian Standar, yang Ada Ujian Matrikulasi Nasional
Negara yang menerapkan kapitalisme di sistem pendidikannya selalu terobsesi dengan pertanyaan berikut: Bagaimana cara memantau kinerja siswa jika tidak diuji secara konstan? Bagaimana bisa meningkatkan pengajaran jika tidak ada pertanggungjawaban ke guru yang 'payah' atau tidak memberikan penghargaan pada guru yang baik? Bagaimana cara menciptakan kompetisi dan melibatkan sektor swasta? Bagaimana cara menciptakan variasi pilihan sekolah kepada orang tua atau pelajar?
Jawaban dari realita Finlandia tampaknya bertentangan dengan mindset orang Amerika ataupun para reformis pendidikan lainnya. Finlandia tidak memiliki ujian nasional pada tiap jenjang pendidikan. Yang ada hanyalah Ujian Matrikulasi Nasional yang diambil pada jenjang sekolah menengah atas yang bersifat 'sukarela'.
Wajib belajar di Finlandia sendiri adalah antara usia 7-16 tahun. SD 6 tahun dan SMP 3 tahun. Setelah lulus SMP, siswa memiliki pilihan boleh langsung masuk dunia kerja atau masuk sekolah persiapan profesi atau gimnasium (setingkat sekolah menengah atas). Lulusan sekolah menengah atas ini nantinya bisa lanjut lagi ke politeknik ataupun universitas. Pada intinya, tidak ada UN SD dan SMP.
Kurikulum Pendidikan yang Fleksibel
Sekolah di Finlandia tidak terikat dengan kurikulum pendidikan yang seragam. Sekolah tidak harus menerapkan kurikulum yang sama dengan metode yang sama pada jadwal yang sama. Kementerian Pendidikan meluncurkan "Kurikulum Dasar" yang fleksibel, semacam panduan umum mengenai mata pelajaran apa yang harus diajarkan dan tujuan yang harus dicapai di setiap tingkat kelas.
Kurikulum Dasar ini berlaku sebagai dasar untuk setiap sekolah saat mereka mempersiapkan kurikulum sendiri, di mana mereka dapat berkreasi menekankan pada pedagogi tertentu, nilai tertentu (misalnya, sekolah hijau), keterampilan (seni, olahraga, bahasa), atau isu-isu lokal (misalnya, sekolah multikultural).
Setiap kelas difasilitasi hingga 3 orang guru. Apa yang guru peroleh dari pendidikannya memberi mereka berbagai macam metode pengajaran yang dapat digunakan sesuka mereka. Keanekaragaman dipandang sebagai kekuatan yang nyata dengan tidak mengisolasi siswa yang berbakat.
Para siswa di Finlandia sangat menikmati belajar, selalu rindu sekolah, tidak rela tidak sekolah hanya karena libur ekstra atau sakit. Sekolah-sekolah di Finlandia sangat sedikit memberikan PR (tidak lebih dari 1/2 jam waktu pengerjaan) dan lebih banyak melibatkan siswanya dalam aktivitas yang lebih kreatif.
Bisa dikatakan guru lah kunci keberhasilan dari sistem sekolah Finlandia, dan individualitas yang diperbolehkan dalam kelas. Para guru melihat siswanya sebagai individu dengan kebutuhan yang berbeda: fokus pada masing-masing anak dan kekuatan serta problem tiap anak.
Guru Memiliki Tanggung Jawab yang Besar
Guru-guru di sekolah negeri Finlandia mendapatkan pelatihan khusus untuk dapat menilai siswa satu kelas menggunakan tes independen yang mereka ciptakan sendiri. Setiap anak mendapatkan kartu rapor tiap akhir semester, tapi rapor ini berdasarkan penilaian individu oleh tiap guru. Secara berkala, Menteri Pendidikan memantau kemajuan nasional dengan menguji beberapa sampel kelompok dari sekolah yang berbeda.
Sistem ini memungkinkan dihasilkannya penilaian yang sangat spesifik ke kemampuan tiap individu anak. Bukan sistem penilaian umum yang mungkin kurang dapat menjangkau kemampuan spesifik tiap anak. Guru dapat mengeluarkan kreatifitasnya untuk memberikan perhatian khusus ke tiap anak. Guru jadi punya tanggung jawab dan peran yang lebih besar.
Kadang seorang guru tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu siswanya tapi dibatasi oleh sistem sekolah yang menyatakan bahwa lebih penting untuk bergerak lanjut mengikuti kurikulum yang ada daripada memperlambat "hanya demi" siswa-siswa yang membutuhkan waktu tambahan dalam menerima pelajaran.
Guru dan staf administrasi sekolah di Finlandia memiliki martabat atau gengsi yang tinggi, gaji yang layak, dan banyak tanggung jawab. Gelar Master (S2) diperlukan untuk menjadi guru. Program pelatihan guru di Finlandia adalah salah satu sekolah profesional yang paling selektif di negara ini. Jika terdapat guru yang performanya buruk, tanggung jawab kepala sekolah untuk menangani hal tersebut.
Kebijakan pendidikan lebih penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan negara daripada ukuran negara tersebut atau keanekaragaman etnis di negara itu. 20 tahun lalu Finlandia adalah negara miskin yang bergantung pada sektor agrikultur. Namun, mereka berhasil bangkit dan membutuhkan waktu hingga satu generasi setelah mereformasi sistem pendidikan negaranya.
Mereka meyakini bahwa kesetaraan dalam pembelajaran dini akan memungkinkan anak-anak untuk menemukan potensi sejati mereka ketika mereka tumbuh dewasa. Bagaimana dengan sistem pendidikan Indonesia? Bapak Ibu mampu untuk membandingkannya sendiri.
*) Sumber bacaan: Lupakan Amerika, Pendidikan di Finlandia yang Terbaik Sedunia
Sumber: http://www.sekolahdasar.net/2013/03/karakteristik-sistem-pendidikan-terbaik.html#ixzz2Nm53d8eB Yandri Soeyono 11:13 PM Indonesia
*tulisan ini merupakan saduran.
Survei yang dilakukan setiap 3 tahun sekali oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2009 menempatkan pelajar Finlandia tetap nyaris teratas pada ketiga kompetensi tersebut. Sementara itu survei global mengenai kualitas hidup oleh Newsweek, Finlandia ditasbihkan sebagai negara dengan kualitas hidup nomor satu di dunia.
Pasi Sahlberg, Direktur Mobilitas Internasional, Departemen Pendidikan Nasional Finlandia telah menulis buku tentang kesuksesan sistem pendidikan Finlandia yang berjudul Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?. Berikut adalah karakteristik sistem pendidikan Finlandia yang terbaik di dunia.
Pilihan Sekolah Sedikit dan Semua Dikelola Pemerintah
Mulai sekolah setingkat TK sampai perguruan tinggi, pelajar-pelajar Finlandia bersekolah di sekolah negeri. Hanya ada sedikit sekolah swasta di Finlandia, dan bahkan semuanya dibiayai pemerintah. Tidak ada yang diperbolehkan untuk membebankan biaya sekolah.
Variasi pilihan sekolah di Finlandia sangat sedikit. Di sana, pilihan sekolah tidak lagi menjadi prioritas utama. Kunci kesuksesan Finlandia dalam memperbaiki sistem pendidikannya adalah mereka tidak mengejar keunggulan akademis (excellence), tapi kesetaraan (equity).
Setiap anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tanpa melihat latar belakang keluarga, pendapatan, atau lokasi geografis. Pendidikan utamanya bukanlah cara untuk menghasilkan individu yang cerdas, tetapi sebagai alat untuk meratakan kesenjangan sosial. Keunggulan akademis bukanlah prioritas khusus bagi Finlandia, tetapi Finlandia berhasil menciptakan keunggulan akademik melalui fokus kebijakan pada kesetaraan.
Finlandia menyediakan sekolah yang sehat dan lingkungan yang aman untuk anak-anak. Mereka menawarkan semua anak makanan sekolah gratis, akses mudah ke perawatan kesehatan, konseling psikologis, dan bimbingan individual.
Tidak Ada Kompetisi di Sekolah Finlandia
Sistem pendidikan Finlandia juga tidak mengenal istilah kompetisi dan sistem peringkat. Tidak ada daftar sekolah terbaik atau guru terbaik di Finlandia. Pendorong utama dari kebijakan pendidikan bukanlah persaingan antar guru dan antar sekolah, tapi kerjasama. Siswa dengan development disorder ataupun penyandang cacat diletakkan pada kelas yang sama dengan siswa umum lainnya. Mereka tidak mengukur prestasi hanya untuk memberi label pada siswa.
Finlandia memandang kompetisi dalam lingkungan pendidikan merupakan konsep yang destruktif. Mental anak dapat dihancurkan oleh evaluasi terus-menerus dan membuat anak-anak kurang percaya diri dengan kemampuannya. Bagi Finlandia, ketika anak-anak dapat unggul pada apa yang mereka dapat lakukan dengan baik, bukan diukur untuk memenuhi standar, mereka dapat menghasilkan performa yang terbaik.
Anak-anak harus diberikan pendidikan sehingga mereka dapat berkembang terlepas dari bakat mereka. Tujuan pendidikan seyogianya dapat membentuk anak menjadi manusia yang lebih baik yang menghargai diri mereka sendiri dan dapat bersosialisasi dalam kehidupan tanpa berpikir bahwa mereka lebih 'pintar' atau sebaliknya, tidak berharga.
Tidak Ada Ujian Standar, yang Ada Ujian Matrikulasi Nasional
Negara yang menerapkan kapitalisme di sistem pendidikannya selalu terobsesi dengan pertanyaan berikut: Bagaimana cara memantau kinerja siswa jika tidak diuji secara konstan? Bagaimana bisa meningkatkan pengajaran jika tidak ada pertanggungjawaban ke guru yang 'payah' atau tidak memberikan penghargaan pada guru yang baik? Bagaimana cara menciptakan kompetisi dan melibatkan sektor swasta? Bagaimana cara menciptakan variasi pilihan sekolah kepada orang tua atau pelajar?
Jawaban dari realita Finlandia tampaknya bertentangan dengan mindset orang Amerika ataupun para reformis pendidikan lainnya. Finlandia tidak memiliki ujian nasional pada tiap jenjang pendidikan. Yang ada hanyalah Ujian Matrikulasi Nasional yang diambil pada jenjang sekolah menengah atas yang bersifat 'sukarela'.
Wajib belajar di Finlandia sendiri adalah antara usia 7-16 tahun. SD 6 tahun dan SMP 3 tahun. Setelah lulus SMP, siswa memiliki pilihan boleh langsung masuk dunia kerja atau masuk sekolah persiapan profesi atau gimnasium (setingkat sekolah menengah atas). Lulusan sekolah menengah atas ini nantinya bisa lanjut lagi ke politeknik ataupun universitas. Pada intinya, tidak ada UN SD dan SMP.
Kurikulum Pendidikan yang Fleksibel
Sekolah di Finlandia tidak terikat dengan kurikulum pendidikan yang seragam. Sekolah tidak harus menerapkan kurikulum yang sama dengan metode yang sama pada jadwal yang sama. Kementerian Pendidikan meluncurkan "Kurikulum Dasar" yang fleksibel, semacam panduan umum mengenai mata pelajaran apa yang harus diajarkan dan tujuan yang harus dicapai di setiap tingkat kelas.
Kurikulum Dasar ini berlaku sebagai dasar untuk setiap sekolah saat mereka mempersiapkan kurikulum sendiri, di mana mereka dapat berkreasi menekankan pada pedagogi tertentu, nilai tertentu (misalnya, sekolah hijau), keterampilan (seni, olahraga, bahasa), atau isu-isu lokal (misalnya, sekolah multikultural).
Setiap kelas difasilitasi hingga 3 orang guru. Apa yang guru peroleh dari pendidikannya memberi mereka berbagai macam metode pengajaran yang dapat digunakan sesuka mereka. Keanekaragaman dipandang sebagai kekuatan yang nyata dengan tidak mengisolasi siswa yang berbakat.
Para siswa di Finlandia sangat menikmati belajar, selalu rindu sekolah, tidak rela tidak sekolah hanya karena libur ekstra atau sakit. Sekolah-sekolah di Finlandia sangat sedikit memberikan PR (tidak lebih dari 1/2 jam waktu pengerjaan) dan lebih banyak melibatkan siswanya dalam aktivitas yang lebih kreatif.
Bisa dikatakan guru lah kunci keberhasilan dari sistem sekolah Finlandia, dan individualitas yang diperbolehkan dalam kelas. Para guru melihat siswanya sebagai individu dengan kebutuhan yang berbeda: fokus pada masing-masing anak dan kekuatan serta problem tiap anak.
Guru Memiliki Tanggung Jawab yang Besar
Guru-guru di sekolah negeri Finlandia mendapatkan pelatihan khusus untuk dapat menilai siswa satu kelas menggunakan tes independen yang mereka ciptakan sendiri. Setiap anak mendapatkan kartu rapor tiap akhir semester, tapi rapor ini berdasarkan penilaian individu oleh tiap guru. Secara berkala, Menteri Pendidikan memantau kemajuan nasional dengan menguji beberapa sampel kelompok dari sekolah yang berbeda.
Sistem ini memungkinkan dihasilkannya penilaian yang sangat spesifik ke kemampuan tiap individu anak. Bukan sistem penilaian umum yang mungkin kurang dapat menjangkau kemampuan spesifik tiap anak. Guru dapat mengeluarkan kreatifitasnya untuk memberikan perhatian khusus ke tiap anak. Guru jadi punya tanggung jawab dan peran yang lebih besar.
Kadang seorang guru tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu siswanya tapi dibatasi oleh sistem sekolah yang menyatakan bahwa lebih penting untuk bergerak lanjut mengikuti kurikulum yang ada daripada memperlambat "hanya demi" siswa-siswa yang membutuhkan waktu tambahan dalam menerima pelajaran.
Guru dan staf administrasi sekolah di Finlandia memiliki martabat atau gengsi yang tinggi, gaji yang layak, dan banyak tanggung jawab. Gelar Master (S2) diperlukan untuk menjadi guru. Program pelatihan guru di Finlandia adalah salah satu sekolah profesional yang paling selektif di negara ini. Jika terdapat guru yang performanya buruk, tanggung jawab kepala sekolah untuk menangani hal tersebut.
Kebijakan pendidikan lebih penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan negara daripada ukuran negara tersebut atau keanekaragaman etnis di negara itu. 20 tahun lalu Finlandia adalah negara miskin yang bergantung pada sektor agrikultur. Namun, mereka berhasil bangkit dan membutuhkan waktu hingga satu generasi setelah mereformasi sistem pendidikan negaranya.
Mereka meyakini bahwa kesetaraan dalam pembelajaran dini akan memungkinkan anak-anak untuk menemukan potensi sejati mereka ketika mereka tumbuh dewasa. Bagaimana dengan sistem pendidikan Indonesia? Bapak Ibu mampu untuk membandingkannya sendiri.
*) Sumber bacaan: Lupakan Amerika, Pendidikan di Finlandia yang Terbaik Sedunia
Sumber: http://www.sekolahdasar.net/2013/03/karakteristik-sistem-pendidikan-terbaik.html#ixzz2Nm53d8eB Yandri Soeyono 11:13 PM Indonesia

Yandri Soeyono | Berita Pendidikan terkini, termasuk info tentang sertifikasi, kurikulum, dan pembelajaran. Konsultasi Materi dan Pembelajaran Matematika.
at
11:13 PM
Roh = Akal dan Hati?
Pada perkuliahan terakhir Filsafat Ilmu (semester ganjil tahun
ajaran 2012/2013), diceritakan/ berbagi pengalaman tentang beberapa hal
termasuk roh, larangan mendahului kehendak Tuhan, Ikhtiar dan Doa. Lebih kepada
spiritual, karena saat mempelajari filsafat, harus diperkuat terlebih dahulu
spiritual masing-masing, demikian anjuran yang kami terima.
Menurut ilmu batin pada diri manusia
terdapat sembilan jenis Roh (sumber: http://terapialkautsar.blogspot.com/2011/06/9-jenis-roh-manusia.html). Masing-masing roh mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ke sembilan macam roh
yang ada pada manusia itu adalah sebagai berikut :
- Roh Idofi (Roh Ilofi) : adalah roh yang sangat utama bagi manusia. Roh Idofi juga disebut JIWA AWAL SUCI, karena roh inilah maka manusia dapat hidup. Bila roh tersebut keluar dari raga, maka manusia yang bersangkutan akan mati. Roh ini sering disebut NYAWA.
- Roh Rabani : Roh yang dikuasai dan diperintah oleh roh idofi. Alamnya roh ini ada dalam cahaya kuning diam tak bergerak. Bila kita berhasil menjumpainya maka kita tak mempunyai kehendak apa-apa. Hatipun terasa tenteram. Tubuh tak merasakan apa-apa.
- Roh Rohani : Roh inipun juga dikuasai oleh roh idofi. Karena adanya roh Rohani ini, maka manusia memiliki kehendak dua rupa. Kadang-kadang suka sesuatu, tetapi di lain waktu ia tak menyukainya. Roh ini mempengaruhi perbuatan baik dan perbuatan buruk. Roh inilah yang menepati pada 4 jenis nafsu, yaitu :
- Nafsu Luwamah (aluamah)
- Nafsu Amarah
- Nafsu Supiyah
- Nafsu Mulamah (Mutmainah).
- Roh Nurani : Roh ini dibawah pengaruh roh-roh Idofi. Roh Nurani ini mempunyai pembawa sifat terang. Karena adanya roh ini menjadikan manusia yang bersangkutan jadi terang hatinya. Kalau Roh Nurani meninggalkan tubuh maka orang tersebut hatinya menjaid gelap dan gelap pikirannya.
- Roh Kudus (Roh Suci) : Roh yang di bawah kekuasaan Roh Idofi juga. Roh ini mempengaruhi orang yang bersangkutan mau memberi pertolongan kepada sesama manusia, mempengaruhi berbuat kebajikan dan mempengaruhi berbuat ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.
- Roh Rahmani : Roh dibawah kekuasaan roh idofi pula. Roh ini juga disebut Roh Pemurah. Karena diambil dari kata Rahman yang artinya pemurah. Roh ini mempengaruhi manusia bersifat sosial, suka memberi.
- Roh Jasmani : Roh yang juga di bawah kekuasaan Roh Idofi. Roh ini menguasai seluruh darah dan urat syaraf manusia. Karena adanya roh jasmani ini maka manusia dapat merasakan adanya rasa sakit, lesu, lelah, segar dan lain-lainnya. Bila Roh ini keluar dari tubuh, maka ditusuk jarumpun tubuh tidak terasa sakit. Kalau kita berhasil menjumpainya, maka ujudnya akan sama dengan kita, hanya berwarna merah.
- Roh Nabati : ialah roh yang mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan badan. Roh ini juga di bawah kekuasaan Roh Idofi.
- Roh Rewani : ialah roh yang menjaga raga kita. Ketika Roh Rewani keluar dari tubuh maka orang yang bersangkutan akan tidur. ketika masuk ke tubuh orang akan terjaga kembali. Bila orang tidur bermimpi dengan arwah seseorang, maka roh rewani dari orang bermimpi itulah yang menjumpainya. Jadi mimpi itu hasil kerja roh rewani yang mengendalikan otak manusia. Roh Rewani ini juga di bawah kekuasaan Roh Idofi. Jadi kepergian Roh Rewani dan kehadirannya kembali diatur oleh Roh Idofi. Demikian juga roh-roh lainnya dalam tubuh, sangat dekat hubungannya dengan Roh Idofi
Dalam situs
tersebut tidak dicantumkan sumber ilmu tersebut, ini hanya sekedar sharing dan
berbagi informasi dari apa yang saya dapat. Tentunya penjelasan mengenai roh di
atas tidak bisa serta-merta diterima begitu saja, namun perlu pendalaman
terhadap kebenaran isinya. Namun menurut saya pribadi, roh itu adalah akal
pikiran dan hati kita sendiri.
Itulah hebatnya
pikiran dan perasaan yang diberikan Tuhan kepada manusia, dapat menembus ruang
dan waktu hingga ke dimensi lain yang jasmani kita tak mampu menjamahnya. Bahkan,
pikiran kita saat sadar pun mungkin tak mampu memikirkan apa yang pikiran kita
lakukan saat di bawah sadar. Subhanallah..
Namun saya
pernah mengalami saat dimana roh saya seakan tidak bersama tubuh saya di saat
sadar. Yaitu saat dimana terjadinya proses refleksi terhadap kejadian dan
pengalaman yang sedang atau telah dilakukan. Saat dimana saya menyimpulkan
bahwa kebahagiaan adalah milik akhirat dan keindahan hanya pada ciptaan Tuhan. Mengapa
demikian? Karena yang ada di dunia ternyata hanyalah kesenangan, sedangkan
kebahagiaan itu abadi. Dan itu bagi mereka yang mendapatkan surgaNya. Demikian halnya
dengan keindahan, hanyalah pada ciptaanNya, manusia mampu membuat sesuatu yang
baik dan bagus namun tak mampu membuat sesuatu yang indah. Dan kesimpulan yang
ada membawa pada tujuan hidup manusia selain beribadah kepada Tuhan juga untuk
menyenangkan orang lain. Memberilah pada sesama, dan meminta hanya kepada
Allah.
Ini adalah
pengalaman saya ketika merasa bahwa pada saat sedang berefleksi, roh saya tidak
berada pada tubuh saya. Apapun yang saya lakukan, tidak terkoordinasi secara
cepat dan langsung dengan pikiran dan perasaan. Apa yang dilakukan serasa tidak
ber-nyawa, karena pikiran dan hati sedang berada pada dimensi lain. Berdasarkan
pengalaman itulah, saya mendefinisikan bahwa Roh itu adalah akal pikiran dan hati/perasaan
dari manusia itu sendiri.
Dan mengutip
dari akhir perkuliahan tersebut, Prof. Dr. Marsigit mengatakan bahwa “kita tidak
boleh mendahului keputusan Allah.. ada waktu untuk belajar ya belajar. Ada waktu
untuk ikhtiar ya ikhtiar. Ada waktu untuk berdoa, ya berdoa. Jangan hentikan
ikhtiar dan doamu..”.
Wassalam..
Yandri Soeyono
NIM : 12709251058
Pendidikan Matematika
Kelas C

Roh = Akal + Hati?
Yandri Soeyono | Berita Pendidikan terkini, termasuk info tentang sertifikasi, kurikulum, dan pembelajaran. Konsultasi Materi dan Pembelajaran Matematika.
at
3:00 AM
FILSAFAT DALAM ILMU PENDIDIKAN
Makalah Dibuat Dalam Rangka
Melengkapi Tugas-Tugas Perkuliahan Filsafat Ilmu Dari Dosen Prof. Dr. Marsigit
BAB
I
PENDAHULUAN
Manusia
adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk
ciptaan Tuhan lainnya. Salah satu indikator dari sempurnanya manusia adalah
dirahmati akal pikiran. Bukan tiada maksud dari Allah memberikan akal pikiran,
selain hati dan perasaan, kepada manusia, namun sebaliknya akal pikiran serta
hati dan perasaan inilah yang nantinya akan memimpin dan mengarahkan segenap
yang ada dan yang mungkin ada di dunia dan menjadi penentu keberadaan manusia
itu sendiri di akhirat nanti.
Manusia
dapat hidup, berkembang, beramal, hingga saatnya kembali ke Penciptanya adalah
karena akal pikiran dan hatinya. Dan segala bentuk perkembangan hidup yang
dialami manusia pada hakekatnya bisa disebut sebagai pendidikan.
Pendidikan
menurut beberapa ahli seperti Langeveld (dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Dasar_Pendidikan)
mendefinisikan sebagai setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada
anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar
cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari
orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku,
putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang
belum dewasa. Sedangkan menurut John Dewey (dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Dasar_Pendidikan),
Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara
intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Ki Hajar Dewantara
mendefinisikan Pendidikan sebagai tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak,
adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada
pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat
dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (http://id.wikipedia.org/wiki/Dasar_Pendidikan).
Namun ada juga yang berpandangan bahwa pendidikan
pada asasnya adalah pengalihan kebudayaan dari satu angkatan ke angkatan lain
dan juga pengembangan manusia. Oleh karena hal ini, maka selain memperhatikan
manusia sebagai sbjek dan objek, pendidikan juga perlu memperhatikan masukan-masukan
eksternal seperti budaya (Stella Van Petten Henderson dalam Imam Barnadib,
2002:1). Kebudayaan di sini memiliki arti yang luas, yaitu segala hasil budi
manusia.
Dalam
makalah ini, penulis mencoba untuk memahami kedudukan Filsafat sebagai ilmu
dalam ilmu lainnya, yaitu Ilmu Pendidikan yang mungkin nantinya contoh-contoh yang
ada adalah dalam Pendidikan Matematika sesuai latar belakang penulis. Kenapa
penulis menulis tentang ini? Karena ini merupakan pikiran dan rasa gelitik yang
menjadi pertanyaan dan keingin-tahuan penulis tentang filsafat itu sendiri.
Pendapat ini dapat disejajarkan dengan pepatah “tak kenal maka tak sayang”.
Tentunya,
penulis berharap penjelajahan ini mampu memberikan penerangan dan jawaban yang
lebih mudah untuk dijelaskan ulang, terutama oleh penulis. Dan juga mampu
membuktikan bahwa penulis berhasil membangun filsafatnya sendiri, minimal untuk
diri penulis sendiri.
BAB
II
MAKNA
FILSAFAT PENDIDIKAN
A. Filsafat
Istilah
filsafat memiliki banyak pengertian, ditinjau dari sisi asal kata maupun
pengertian menurut para filsuf. Ditinjau dari asal kata, pengertian istilah
filsafat yang umum digunakan adalah berasal dari kata philein yang berarti cinta atau suka sekali akan sesuatu dan kata sophia yang berarti kebijakan atau
kebajikan (Imam Barnadib, 2002:4). Namun juga ada yang berpendapat bahwa dalam
istilah filsafat kata kuncinya bukan pada kebijaksanaan, tetapi kebenaran,
sehingga kata filsafat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan atau cinta kebenaran
(Soegiono,dkk, 2012:5).
Selain
berdasarkan asal kata, beberapa filsuf terkenal juga memberikan pengertiannya
sendiri tentang filsafat (Soegiono,dkk, 2012:5), seperti :
a. Menurut
Plato, “Filsafat adalah pengetahuan yang berminat mancapai kebenaran asli”.
b. Aristoteles
mengartikan filsafat sebagai “ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang
tergabung di dalamnya metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan
estetika”.
c. Bernard
Russel mengartikan filsafat sebagai “the atttend to answer ultimate question
critically”.
d. William
James mengartikan filsafat sebagai “a collective name for question which have
not
answered to the satisfaction of all that have asked them”.
e. Sedangkan
Al-Farabi memakai makna filsafat sebagai pengetahuan tentang hakikat yang
sebenarnya.
f. Immanuel
Kant mengartikan filsafat sebagai pengetahuan yang menjadi pangkal pokok segala
pengetahuan yang tercakup di dalamnya apa yang dapat diketahui (metafisika),
apa yang seharusnya diketahui (etika), sampai di mana harapan kita (agama), apa
itu manusia (antropologi).
Dan
pengertian filsafat berdasarkan perkuliahan Filsafat Ilmu yang diampu oleh Prof.
Dr. Marsigit adalah sebagai olah pikir yang refleksif yang meliputi ontologi
(hakikat), epistemologi (metode), dan aksiologi (nilai).
Secara
sederhana dapat penulis artikan bahwa filsafat adalah alam dan kehidupan, yang
ada dan yang mungkin ada yang dipikirkan dan dirasakan oleh manusia. Ini
merupakan salah satu bentuk ibadah manusia terhadap Pencipta atas karunia akal
pikiran yang telah diberikan. Begitu besar pengaruh akal dan pikiran manusia
hingga ia mampu mempengaruhi fisik jasmani manusia. Itulah filsafat.
B. Pendidikan
dan Filsafat
Pendidikan
sebagai pengetahuan atau ilmu mempunyai bagian yang terdiri atas dasar dan
fakta. Lazimnya, dasar bersifat abstrak. Misal, pendidikan di Indonesia
berdasarkan Pancasila. Yang dimaksud dengan Pancasila adalah nilai-nilai luhur
yang bersumber dari Pancasila. Ada banyak nilai-nilai luhur, kita misalkan
adalah keadilan. Keadilan ini bersifat abstrak. Keadilan akan bersifat konkret
jika sudah diterapkan dalam bidang tertentu, misalkan dalam bidang hukum.
Inilah yang disebut fakta dari pendidikan.
Dalam
pendidikan, manusia adalah subjek pendidikan. Pendidikan perlu mengetahui
dengan jelas pengertian manusia. Apa itu
manusia? Jawaban dari pertanyaan ini dapat bersifat umum yang lebih abstrak
kemudian akan diperjelas dengan penjelasan yang lebih konkret. Dan inilah
filsafat.
Jawaban
secara umum, misal, manusia adalah makhluk monodualis, mono-multidimensional.
Maka penjabaran yang lebih khusus untuk manusia sebagai makhluk monodualis
adalah makhluk yang terdiri atas jiwa dan raga yang keduanya tidak terpisah
satu sama lainnya. Keduanya saling menunjang dan saling berhubungan serta
saling berketergantungan. Manusia sebagai makhluk mono-multidimensional
memiliki arti sebagai manusia yang terdiri dari berbagai komponen, jiwa-raga,
tampak dan tidak tampak, serta mempunyai sifat yang bermacam-macam. Namun semua
itu menyatu dalam suatu ikata sehingga pada hakekatnya manusia mempunyai
pribadi yang utuh dan tunggal.
Contoh
lain hubungan antara filsafat dan pendidikan adalah metode atau cara mengajar.
Mengajar adalah cara guru menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik. Cara
mengajar inilah yang memerlukan filsafat agar didapatkan cara terbaik untuk
mengajar. Misal jika pengetahuan kita cari maknanya berdasarkan
sumber-sumbernya maka akan muncul beberapa jenis pengetahuan.
Pengetahuan
yang bersumber pada wahyu yang berasal dari Tuhan (agama). Karena manusia
merupakan penganut agama maka yang diharapkan dari belajar agama adalah agar
manusia semakin beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, selain mentransfer ilmu,
guru tersebut harus dapat meningkatkan iman dan ketakwaan peserta didiknya.
Sehingga, dalam mengajarkan pendidikan yang bersumber dari Tuhan maka perlu
dihindarkan dari kemungkinan timbulnya keragu-raguan dari peserta didik.
Lain
halnya jika pengetahuan bersumber dari pengalaman, seperti pengetahuan alam.
Pengetahuan ini bersumber dari pengamatan atau observasi yang teratur.
Sehingga, guru harus dapat mengajarkan ilmu dengan pengamatan secara langsung
pula, sehingga peserta didik memiliki pengalaman yang analog ataupun mirip
dengan ilmu yang diajarkan.
Contoh-contoh
di atas merupakan penggambaran hubungan antara filsafat dengan pendidikan.
Secara tersirat telah digambarkan di atas bagaimana kita berpikir metafisika
untuk melihat manusia sebagai monodualis dan mono-multidimensional hingga guru bisa
merefleksikan bagaimana sebaiknya mendidik siswa. Dan contoh selanjutnya adalah
pemikiran filsafat dari sisi epistemologi. Bagaimana melihat pengetahuan dari
cara mendapatkan ilmu itu sendiri, sehingga dalam mengajar pun guru mampu
menyesuaikan dengan cara ilmu dan pengetahuan itu diperoleh.
Logika
adalah bagian dari filsafat. Salah satu filsuf yang mengembangkan logika adalah
Russel dengan hukum sebab-akibat dalam koherensi. Dan salah satu tujuan
pendidikan adalah untuk mencerdaskan bangsa. Salah satu kemungkinan untuk
mengembangkan kecerdasan peserta didik adalah meningkatkan kemampuan berpikir
logis.
Aspek
lain dari filsafat adalah aksiologi yang membahas tentang nilai. Ada dua nilai,
yaitu etika dan estetika. Etika adalah mengenai baik buruk ditinjau dari
tingkah laku manusia dan estetika adalah mengenai keindahan. Kedua aspek ini
pun perlu hadir dalam pendidikan.
Etika
perlu ditegakkan dalam hidup bermasyarakat dan bersosialisasi. Sehingga etika
wajib dalam suatu pendidikan agar tercipta kehidupan yang harmonis dan
serasi. Dalam filsafat ada beberapa
pendekatan tentang hal ini, yaitu pendekatan konsekuensialis dan
nonkonsekuensialis (Imam Bernadib, 2002:9).
Pendekatan
yang menyatakan bahwa sesuatu itu baik jika hasilnya menunjukkan kebaikan
adalah pendekatan yang konsekuensialis. Misal adalah memakan makanan yang
bergizi dianggap baik jika yang dimakan dapat berakibat baik bagi kesehatan.
Sedangkan pendekatan nonkonsekuensialis tidak melihat baik-buruknya pada hasil
melainkan pada landasan ideal yang menjadi dasar perbuatan. Menurut pandangan
ini, setiap manusia memiliki watak atau panggilan hati untuk berbuat baik. Dan
tingkah laku manusia bergantung dari panggilan hatinya tersebut.
Dari
beberapa contoh di atas, dapat terlihat bahwa antara filsafat dan pendidikan
memiliki hubungan dan saling melengkapi. Filsafat dapat dijadikan sebagai
metode, atau untuk mempelajari subjek maupun objek pendidikan, berfleksi untuk
perubahan lebih baik, pengembangan atas nilai-nilai dalam pendidikan, dan
sebagai konsep dasar pendidikan itu sendiri.
C. Makna
Filsafat Pendidikan (review “Filsafat Pendidikan”, Imam Barnadib, 2002)
Dalam
bukunya, Filsafat Pendidikan, Imam Barnadib melihat makna Filsafat Pendidikan
dari beberapa sudut pandang, termasuk hubungan linear dan nonlinear antara
filsafat dan pendidikan. Dari sudut pandang linear diberikan contoh 3 aliran
filsafat terhadap pendidikan yaitu idealisme, realisme, dan pragmatisme
kemudian menelaahnya terhadap aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologinya.
Selanjutnya beliau mencoba memberi gambaran yang lebih luas dengan menganalisis
hubungan antara filsafat dan pendidikan yang nonlinear untuk melihat apa dan
bagaimana filsafat pendidikan itu.
Dengan
review tersebut, penulis akan mencoba mencari jawaban dari pertanyaan awal
kenapa makalah ini dibuat. Harapannya adalah, mereview pandangan atau referensi
yang ada dapat memberikan wawasan kepada penuli tentang filsafat dan filsafat
pendidikan itu sendiri. Keterbatasan adalah motivasi utama dalam ikhtiar saya
untuk menulis makalah ini.
Sudut
pandang pertama mengatakan bahwa filsafat pendidikan dapat tersusun karena
adanya hubungan linear antara filsafat dan pendidikan. Misal, aliran filsaat
idealisme menjadi filsafat pendidikan idealisme, aliran realisme menjadi
filsafat pendidikan realisme, dan aliran pragmatisme menjadi filsafat
pendidikan pragmatisme.
Idealisme
memandang kenyataan dan kebenaran sesuatu pada hakekatnya sama kualitasnya
dengan hal-hal yang spritual atau ide-ide. Pendidikan yang menitik-beratkan
pada idealisme akan merumuskan tujuan pendidikan sebagai pencapaian manusia
yang berkepribadian mulia dan memiliki taraf kerohanian yang tinggi dan ideal.
Jika
yang digunakan sebagai pegangan adalah aliran realisme maka tujuan pendidikan
akan dirumuskan sebagai upaya pengembangan potensi-potensi yang ada pada
peserta didik. Karena menurut realisme, yang dimaksud dengan hakekat itu berada
pada benda, bukan sesuatu yang lepas dari pemiliknya.
Bagi
pendidikan yang berlandaskan pragmatisme, rumusan tujuan pendidikan yang ingin
dicapai adalah peserta didik yang berilmu pengetahuan banyak dan berguna.
Karena menurut pragmatisme, kenyataan dan kebenaran itu pada hakekatnya adalah
hal-hal yang berfungsi atau berguna.
Secara
ontologi, maka makna filsafat pendidikan pragmatisme akan mendeskripsikan bahwa
kenyataan itu bukanlah sesuatu yang mutlak. Pragmatisme meyatakan bahwa
kenyataan itu selalu dalam proses menjadi: it
is the process of the making. Oleh karena itu, jawaban dari apa pendidikan
itu, bukanlah sesuatu yang tetap selama-lamanya, melainkan perlu dihayati dan
diinterpretasikan dari waktu ke waktu.
Pertanyaan
tentang pengetahuan yang bagaimana (epistemologi) yang perlu diberikan kepada
peserta didik? Jawabannya bukanlah pengetahuan yang abstrak, melainkan yang
berhubungan dengan pengalaman. Pertanyaan selanjutnya mengenai nilai-nilai
bagaiman yang perlu dijadikan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan? Maka
jawabannya bukanlah hal-hal yang bersifat ideal, melainkan yang lebih mengarah
pada hal-hal instrumental. Misal, nilai-nilai yang mau diajarkan seperti
kejujuran, keadilan dan lain-lain hendaknya dihindari pada pengajaran yang bersifat
verbal, namun sedapat mungkin hal tersebut ditunjukkan dengan contoh-contoh
yang nyata terutama yang lazim ditemui.
Tinjauan
dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini terhadap aliran idealisme
dan realisme pun sama halnya dengan contoh dari aliran pragmatis di atas. Akan
terdapat perbedaan secara mendasar dari ketiga aliran ini.
Bahasan
berikut ini akan melihat dari sudut pandang nonliner antara filsafat dan
pendidikan. Tinjauan nonlinear perlu ditampilkan bila membicarakan filsafat
dalam ruang lingkup permasalahan pendidikan. Misal, bagaimana pendidikan dapat
mengembangkan konsep yang mencerminkan jawaban atas pertanyaan tentang
tantangan teknologi komunikasi dan informasi sekarang ini.
Jawaban
yang dicari dan dikembangkan dari pertanyaan itu tidaklah sederhana karena
harus ditelaah dulu makna teknologi informasi dan komunikasi, kondisi
pendidikan dan pengembangan konsep yang relevan.
Dengan
adanya perangkat komunikasidan teknologi informasi sekarang ini, tentu saja
manusia akan merasa kebanjiran berbagai informasi dan pengetahuan lainnya.
Sehingga, peserta didik perlu disiapkan agar mampu menghadapi banjir informasi
tersebut. Peserta didik diharapkan bukan hanya sebagai penerima melainkan juga
sebagai orang yang mampu menyeleksi mana yang perlu diketahui dan dipelajari.
Dalam konteks ini, peserta didik diharapkan memiliki kepribadian yang mantap
dan mandiri. Ini adalah pemikiran dari aspek ontologi.
Jika
informasi yang masuk adalah ilmu, maka begitu banyak ilmu yang membanjiri
peserta didik kita, sehingga ilmu itu jangan hanya dilihat sebagai pengetahuan
saja, tetapi harus mampu dimanfaatkan. Jadi makna belajar bukanlah hanya
sebatas maintainance learning tetapi sebagai innovative learning. Ini adalah
dari sisi epistemologi.
Selanjutnya
aspek aksiologi yang perlu diperhatikan adalah kedua teknologi tersebut telah
menghasilkan suatu budaya. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan adalah
apakah budaya baru itu sudah seyogyanya diterima atau tidak, sesuai aspek
positif dan negatif yang ditimbulkan.
BAB
III
ALIRAN
FILSAFAT PENDIDIKAN
Pada
bab terdahulu telah diuraikan beberapa contoh aliran dalam filsafat yang
memiliki hubungan linear dengan pendidikan, yaitu idealisme yang menjadi
filsafat pendidikan idealisme, filsafat realisme menjadi filsafat pendidikan
realisme, dan filsafat pragmatisme menjadi filsafat pendidikan pragmatisme.
Pada bab ini akan dibahas beberapa aliran filsafat pendidikan lainnya sebagai
gambaran yang lebih jelas hubungan antara filsafat dan pendidikan.
Ada
dua kelompok besar filsafat pendidikan, yaitu filsafat pendidikan “progresif”
dan filsafat pendidikan “ Konservatif”. Yang pertama didukung oleh filsafat
pragmatisme dari John Dewey, dan romantik naturalisme dari Roousseau. Yang
kedua didsari oleh filsafat idealisme, realisme humanisme (humanisme rasional),
dan supernaturalisme atau realisme religius. Filsafat-filsafat tersebut
melahirkan filsafat pendidikan esensialisme, perenialisme, dan sebagainya.
Berikut
aliran-aliran dalam filsafat pendidikan:
1. Filsafat
Pendidikan Materialisme
Materialisme
berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual atau
supernatural.
Beberapa tokoh yang
beraliran materialisme: Demokritos, Ludwig Feurbach
2. Filsafat
Pendidikan Eksistensialisme
Filsafat ini
memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individu. Secara umum, eksistensialisme
menekankn pilihan kreatif, subjektifitas pengalaman manusia dan tindakan
kongkrit dari keberadaan manusia atas setiap skema rasional untuk hakekat
manusia atau realitas.
Beberapa tokoh dalam
aliran ini : Jean Paul Satre, Soren Kierkegaard, Martin Buber, Martin
Heidegger, Karl Jasper, Gabril Marcel, Paul Tillich
3. Filsafat
Pendidikan Progresivisme
Progresivisme bukan
merupakan bangunan filsafat atau aliran filsafat yang berdiri sendiri, melainkan
merupakan suatugerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran
ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar
di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak bukannya memfokuskan
pada guru atau bidang muatan.
Beberapa tokoh dalam
aliran ini : George Axtelle, william O. Stanley, Ernest Bayley, Lawrence
B.Thomas, Frederick C. Neff
4. Filsafat
Pendidikan esensialisme
Esensialisme adalah
suatu filsafat pendidikan konservatif yang pada mulanya dirumuskan sebagai
suatu kritik pada trend-trend progresif di sekolah-sekolah. Mereka berpendapat
bahwa pergerakan progresif telah merusak standar-standar intelektual dan moral
di antara kaum muda.
Beberapa tokoh dalam
aliran ini: william C. Bagley, Thomas Briggs, Frederick Breed dan Isac L.
Kandell.
5. Filsafat
Pendidikan Perenialisme
Merupakan suatu aliran
dalam pendidikan yang lahir pada abad kedua puluh. Perenialisme lahir sebagai
suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Mereka menentang pandangan
progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Perenialisme
memandang situasi dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian, dan
ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual dan sosio
kultual. Oleh karena itu perlu ada usaha untuk mengamankan ketidakberesan
tersebut, yaitu dengan jalan menggunakan kembali nilai-nilai atau
prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kukuh, kuat dan
teruji.
Beberapa tokoh
pendukung gagasan ini adalah: Robert Maynard Hutchins dan ortimer Adler
6. Filsafat
Pendidikan rekonstruksionisme
Rekonstruksionisme
merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini lahir didasarkan
atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri
dengan masalah-masalah masyarakat yang ada sekarang. Rekonstruksionisme
dipelopori oleh George Count dan Harold Rugg pada tahun 1930, ingin membangun
masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil.
Beberapa tokoh dalam aliran ini:
Caroline Pratt, George Count, Harold Rugg.
Dari
bahasan sekilas tentang beberapa aliran di atas, tentunya jika dilihat dari
aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologinya akan memiliki perbedaan yang
mendasar antara aliran yang satu dengan lainnya. Dan jika diimplementasikan
pada pendidikan atau sistem pendidikan yang ada akan menjadi filosofi atau
ideologi atau pedoman dalam pelaksanaannya.
BAB IV
KESIMPULAN
Pengalaman yang kita miliki adalah filsafat. Mengapa? Karena pengalaman yang kita alami akan menjadi pengetahuan bagi diri kita masing-masing. Pengalaman itu akan menjadi ilmu baru dengan dimensi berpikir intensif dan ekstensif yang berbeda dari tiap individu.
Penulis
mengatakan hal di atas karena tanpa mempelajari Filsafat terlebih dahulu, namun
ternyata, apa yang penulis lakukan (mengajar) adalah bagian dari filsafat yang
telah diuraikan sebelumnya.
Dan
pengalaman yang saya peroleh (karena berlatar belakang Matematika Murni) telah
membentuk pola saya dalam meyakini pendidikan matematika, cara mengajar
matematika di kelas, dan bagaimana menilai proses dan memberikan nilai-nilai
kepada peserta didik. Penulis akui hal tersebut.
Secara
pribadi, hubungan dan manfaat serta kedudukan filsafat dalam matematika maupun
pendidikan matematika telah terlihat dengan cukup jelas dengan merefleksikan
apa yang telah penulis lakukan sebelum ini dan dibandingkan dengan ilmu baru
yang penulis dapatkan pada perkuliahan Filsafat Ilmu dan ikhtiar penyusunan
makalah ini. Bahkan saat ini, penulis bisa menggolongkan diri sendiri ke dalam
aliran filsafat pendidikan yang ada.
Mengikuti
dunia pendidikan beberapa tahun ini, di Indonesia bahkan secara umum di dunia,
terjadi perubahan paradigma dalam sistem pendidikan yang ada di tiap negara.
Dan secara filsafat pastinya terjadi perubahan aliran yang dijadikan acuan. Dan
bagi para guru selaku ujung tombak pendidikan yang berinteraksi secara langsung
dengan peserta didik, seyogyanya mengenal, memahami, menerima, dan ikut
mengimplementasikan perubahan paradigma yang ada. Dan filsafat akan membantu
guru untuk mengenal, memahami, dan mengimplementasikan paradigma yang
diharapkan dalam langkah nyata metode dan model pembelajaran di kelas.
Filsafat
dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang saling mengisi. Dengan
berfilsafat, guru akan dapat melihat masalah dari tempat yang lebih tinggi secara
keseluruhan, dapat mengontrol, inilah manfaat dari olah pikir yang refleksif. Filsafat
adalah otak dan hati dari suatu bentuk tubuh yang dalam hal ini adalah sistem
pendidikan.
DAFTAR
PUSTAKA
Bernadib, Imam., 2002, Filsafat Pendidikan, Yogyakarta, Adicipta
Karya Nusa
Soegiono, H., Muis, Tamsil., 2012, Filsafat Pendidikan Teori dan Praktek,
Surabaya, Remaja Rosdakarya
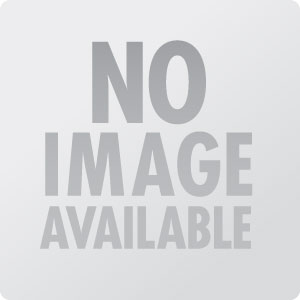
Filsafat Dalam Ilmu Pendidikan
Yandri Soeyono | Berita Pendidikan terkini, termasuk info tentang sertifikasi, kurikulum, dan pembelajaran. Konsultasi Materi dan Pembelajaran Matematika.
at
5:49 PM
INTUISI DALAM MATEMATIKA
SEKOLAH
Refleksi dari
Perkuliahan Filsafat Ilmu Prof. Dr. Marsigit dan pembelajaran dari Elegi Pemberontakan
Pendidikan Matematika pada http://powermathematics.blogspot.com/
Matematika, menurut Imanuel Kant,
akan menjadi ilmu jika dia dibangun atas dasar intuisi ruang dan waktu. Jadi,
menurutnya, matematika sebagai pure logic
belumlah menjadi ilmu karena baru dipandang sebagai a priori saja, masih bersifat
analitik, dan belum sintetik.
 Pure logic/knowledge itu hukumnya subjek sama dengan predikat. Dan ini
hanya ada dalam pikiran manusia, karena sebenarnya tidak ada yang sama di dunia
ini (relatif terhadap ruang dan waktu). Pure
logic merupakan pengandaian dalam pikiran manusia.
Pure logic/knowledge itu hukumnya subjek sama dengan predikat. Dan ini
hanya ada dalam pikiran manusia, karena sebenarnya tidak ada yang sama di dunia
ini (relatif terhadap ruang dan waktu). Pure
logic merupakan pengandaian dalam pikiran manusia.
Sedangkan dalam sintetik,
predikat tidak sepenuhnya termuat dalam subjek. Dengan kata lain ini adalah empirical knowledge, lebih kepada
pengalaman. Kebenaran dalam empirical
knowledge lebih bersifat korespondensi dan selalu kontradiktif secara
filsafat karena dibangun atas dasar kerangka ruang dan waktu.
Maka menurut Kant, matematika
akan menjadi ilmu dan bermanfaat jika jika dia bersifat sintetik a priori. Matematika sebagai pure logic yang bersifat analitik, dikorespondensikan ke dunia
nyata dalam ruang dan waktu berdasarkan pengalaman atau intuisi, inilah
matematika sebagai suatu ilmu.
Andaikan kita sepaham dengan
Imanuel Kant dalam memandang matematika sebagai suatu ilmu yang bersifat
sintetik a priori, maka penanaman konsep matematika yang bersifat formal pada
anak (siswa) haruslah dibangun dalam kerangka ruang dan waktu, berdasarkan
pengalaman dan intuisi siswa. Siswa harus mampu membangun pengalaman mereka
sendiri, mampu membangun intuisi mereka sendiri, dan mampu membangun
pengetahuan mereka sendiri, dan kemudian difasilitasi oleh pendidiknya ke dalam
bentuk matematika yang lebih formal (matematika konsep). Inilah yang disebut
sebagai Architectonic Mathematics.
 Sejalan dengan hal ini, Ebutt dan
Straker (1995) mendefinisikan matematika
sekolah sebagai kegiatan mencari pola, kegiatan problem solving, kegiatan
investigasi dan kegiatan berkomunikasi. Inilah yang membedakan pembelajaran matematika
pada orang dewasa dan pada anak-anak (siswa). Matematika sekolah dalam
pengertian Ebbutt dan Straker, lebih merupakan kegiatan dalam membangun
pengetahuan tentang matematika itu sendiri. Lebih mengedepankan intuisi dan
pengalaman dalam proses pembelajaran karena menggunakan intuisi dan pengalaman yang
dimiliki siswa sebelumnya untuk menemukan pengetahuan baru yang nantinya akan
menjadi intuisi bagi mereka. Hal ini akan terus berkembang dan membentuk
matematika formal dalam pikiran siswa, yang membantu mereka dalam proses
pembelajaran orang dewasa nantinya.
Sejalan dengan hal ini, Ebutt dan
Straker (1995) mendefinisikan matematika
sekolah sebagai kegiatan mencari pola, kegiatan problem solving, kegiatan
investigasi dan kegiatan berkomunikasi. Inilah yang membedakan pembelajaran matematika
pada orang dewasa dan pada anak-anak (siswa). Matematika sekolah dalam
pengertian Ebbutt dan Straker, lebih merupakan kegiatan dalam membangun
pengetahuan tentang matematika itu sendiri. Lebih mengedepankan intuisi dan
pengalaman dalam proses pembelajaran karena menggunakan intuisi dan pengalaman yang
dimiliki siswa sebelumnya untuk menemukan pengetahuan baru yang nantinya akan
menjadi intuisi bagi mereka. Hal ini akan terus berkembang dan membentuk
matematika formal dalam pikiran siswa, yang membantu mereka dalam proses
pembelajaran orang dewasa nantinya.
Apakah siswa tidak bisa diajarkan
pure knowledge? Tentu saja bisa, dan
hal ini telah dan tengah berlangsung pada proses pembelajaran di
sekolah-sekolah, termasuk pada Sekolah Dasar. Apa yang terjadi? Ada dua
kemungkinan. Siswa akan kehilangan intuisi mereka. Pengalaman mereka menjadi
tidak berarti dan hanya mengejar nilai. Atau bahkan yang terjadi adalah siswa
lebih menyukai pengalaman mereka dan menganggap matematika sebagai ilmu yang
membosankan dan tidak menarik sehingga siswa semakin menjauh dari matematika.
Sungguh sangat disayangkan, jika
para matematikawan merasa matematika sebagai suatu ilmu yang wajib dipahami dan
dipelajari oleh setiap manusia karena manfaat dan ketergunaannya dalam
kehidupan, tapi kenyataannya matematika semakin menjadi momok bagi siswa karena
paradigma dari para guru dan pembuat kebijakan bahwa matematika itu adalah
sebatas konsep dan aksioma. Perubahan paradigma sangat diperlukan saat ini
untuk merubah perilaku kita terhadap matematika sekolah, terhadap proses
pembelajaran, dan terhadap siswa (harapannya).
Intuisi dan pengalaman akan lebih
bermakna pada seorang anak atau siswa karena pengalaman itulah yang mereka
alami, intuisilah yang mereka bentuk sendiri dalam pikiran mereka. Pengalaman lebih
dekat dengan siswa dibandingkan sederetan definisi dan teori yang menggunakan
bahasa yang mungkin belum mereka pahami sepenuhnya. Ketakutan terbesar seorang
pendidik seharusnya adalah ketika ilmu yang dia ajarkan pada siswa dapat
dikenal oleh siswa namun siswanya tidak paham untuk apa ilmu ini. Apa kegunaan
dan kapan harus saya gunakan. Pertanyaan lain akan muncul, yaitu untuk apa kita
pelajari hal ini??
Ini telah menjadi bahan renungan
pribadi. Semoga bermanfaat. Amienn..
Yandri Soeyono
NIM : 12709251058
Pendidikan Matematika
Kelas C
Yandri Soeyono 2:18 PM Indonesia

Intuisi dalam Matematika Sekolah
Yandri Soeyono | Berita Pendidikan terkini, termasuk info tentang sertifikasi, kurikulum, dan pembelajaran. Konsultasi Materi dan Pembelajaran Matematika.
at
2:18 PM
Filsafat dan Pendidikan
Mempelajari filsafat tidak bisa
lepas dari mempelajari perjalanan filsafat sejak zaman Yunani kuno dengan
tokoh-tokoh besarnya hingga sekarang ini. Tentu, pada awalnya manusia melakukan
sesuatu dengan tanpa mengerti apa sebenarnya yang dia lakukan, layaknya seorang
anak kecil. Masih menggunakan nalurinya. Inilah yang dinamakan mitos.
Pada zaman Yunani kuno masih terdapat
banyak mitos karena mereka sudah mengenal dewa-dewa pada zaman itu. Hingga lahir
filsuf-filsuf besar yang berkarya menghasilkan banyak pemikirannya, termasuk pemikiran
dalam cara berinteraksi dan berbudaya. Misal Plato, yang telah mampu membuat buku
Republik, yang di dalamnya telah mengatur tentang cara-cara berinteraksi.
Namun, sejak abad I, yang ditandai
dengan lahirnya Jesus Kristus, peradaban pada zaman Yunani kuno mulai berkiblat
pada gereja. Dapat dikatakan bahwa kiblat kebenaran dan segala aturan ada pada
gereja. Sehingga, jika ada penyimpangan pendapat oleh masyarakat terhadap
pendapat gereja, maka akan mendapat pertentangan yang sangat besar. Terlihat dari
apa yang terjadi pada Galileo dan Copernicus.
Sejak abad V, lahirlah Islam. Dan
dominasi gereja pun sudah mulai berkurang pada saat itu. Kebenaran bukan hanya
milik gereja dan kebenaran adalah hak prerogatif dari tiap individu. Islam memiliki
peran sebagai peradaban yang menyelamatkan karya-karya besar filsuf pada zaman Yunani
kuno hingga pada zaman Islam itu juga, seperti karya-karya Imam Ghazali,
sehingga dapat dipelajari hingga sekarang.
Setelah itu dimulailah zaman
modern. Di mana setiap individu memiliki hak untuk berpikir. Pada zaman ini
juga dimulailah era industri di Inggris yang ditandai dengan ditemukannya mesin
uap. Perkembangan dari era industri ini memunculkan
kapitalisme. Jadi dapat dikatakan bahwa Sang Powernow pun sebenarnya dimulai
sejak era ini.
Dan dalam dunia pendidikan pun, terdapat
pengaruh dari industrialisasi dan kapitalisme. Paul Ernest memetakan dunia
pendidikan dalam 5 dunia, yaitu dunia industrialis
(mengedepankan industri, kapitalis dan teknologi), konservatif (yang masih mempertahankan dengan nilai-nilai lama), old-humanis (berpusat pada manusia,
komunis termasuk di dalamnya), progresif
(berorientasi ada hasil), dan sosio-konstruk
(berorientasi pada sosial dan perkembangan siswa).
Bagaimana dengan pendidikan di
Indonesia? Secara umum Indonesia masih terpengaruh oleh kapitalis dan
industrialis. Budaya kapitalis menjadi kiblat dari paradigma anak bangsa dan
keluarga Indonesia. Saat ini isu tentang sosio-konstruk dalam pendidikan sangat
marak dibicarakan, namun sosialisasi dan keinginan berubah dari masyarakat
Indonesia sangat kurang. Hal baru dianggap sebagai masalah dan beban karena
harus berinovasi lagi dalam proses pembelajaran.
Bentuk pembelajaran tradisional
yang lebih berpusat pada guru dianggap masih merupakan pembelajaran yang terbaik.
Jadi siswa hanya menerima ilmu dari guru, kemudian melatihnya dengan soal-soal
latihan. Proses seperti ini telah merenggut intuisi dari siswa. Hal ini tidak
boleh terus berlanjut. Dalam kuliah Filsafat Ilmu, Prof. Dr. Marsigit selalu
menyarankan kepada mahasiswa, guru dan calon guru, agar rebut kembali intuisi. Karena
anak kecil belajar menggunakan intuisi.
Yandri Soeyono
NIM : 12709251058
Pendidikan Matematika
Kelas C
Yandri Soeyono
3:22 PM
Indonesia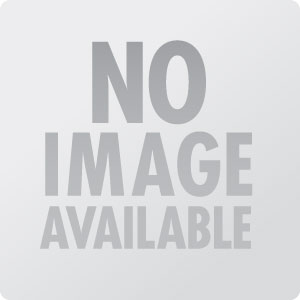
Yandri Soeyono | Berita Pendidikan terkini, termasuk info tentang sertifikasi, kurikulum, dan pembelajaran. Konsultasi Materi dan Pembelajaran Matematika.
at
3:22 PM
MENGAJAR, MENGEJAR
INTUISI
Sebagai refleksi dari kuliah Filsafat Ilmu pada tanggal 8 November 2012,
yang diampu oleh Prof. Dr. Marsigit, saya ingin mengutarakan bahasan tentang
intuisi. Karena selain mendapatkan pengertian dan ilmu tentang intuisi, beliau
pun menganjurkan untuk menggunakan intuisi dalam pembelajaran matematika.
Tidak perlu menjelaskan bilangan 2 (dua) menggunakan definisi konsep yang
kadang atau bahkan sering semakin menyulitkan siswa. Tetapi menggunakan
pengalaman siswa yang telah terkonstruk di pikirannya entah secara sadar
ataupun tidak. Hal ini bersesuaian dengan pandangan konstruktivisme dalam teori
pendidikan.
Ada pengalaman saya tentang siswa SD yang tidak mampu melakukan operasi
penjumlahan dan penguruangan untuk bilangan yang kurang dari 100. Akan tetapi,
mampu melakukan perhitungan dengan cepat untuk bilangan yang jauh lebih besar.
Dia dengan cepat mampu menjawab kembalian sebesar Rp. 1.225,00 jika total harga
barang adalah Rp. 3.775,00 dengan uang konsumen sebesar Rp. 5.000,00. Berbeda
halnya ketika guru bertanya “berapa hasil dari 50-37?”.
Siswa, dengan pengalamannya sendiri, memiliki ilmu dan cara pandang
sendiri terkait sesuatu ilmu. Dan matematika cukup erat kaitannya dengan
hal-hal yang konkrit maupun nyata yang ada dalam kehidupan sehari. Seharusnya,
guru mampu mengkoneksikan antara kedua hal tersebut, yaitu antara pengalaman
yang mungkin dimiliki siswa dan konsep matematika itu sendiri.
“jika engkau ingin menjadi guru matematika yang baik,
sadarlah, kembangkan intuisimu”, demikian ajuran dari Prof. Dr. Marsigit pada
kuliah Filsafat Ilmu pada Program Pascasarjana UNY. Merujuk pada contoh di
atas, tentu ini bukan anjuran kosong. Siswa tersebut tentunya akan mampu untuk
paham dan lebih cepat menjawab sebuah masalah konsep matematika ketika guru
mampu menjelaskan konsep matematika kepada hal-hal yang dekat dengan siswa.
Sangatlah tidak logis ketika siswa mampu melakukan perhitungan dengan bilangan
besar akan tetapi tidak mampu melakukan perhitungan dengan bilangan yang lebih
kecil. Padahal, sistem perhitungan dan metode penyelesaiannya sama. Inilah
tantangan guru untuk dapat mengkoneksikan kedua hal tersebut. Ketika hal sulit
tersebut terlewati, maka kemudahan akan diperoleh sang guru dalam upaya
mencerdaskan bangsa, dalam hal ini adalah siswa-siswa yang dia ajar.
Yandri Soeyono 6:57 PM Indonesia
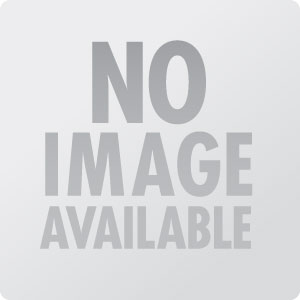
Menggapai Intuisi
Yandri Soeyono | Berita Pendidikan terkini, termasuk info tentang sertifikasi, kurikulum, dan pembelajaran. Konsultasi Materi dan Pembelajaran Matematika.
at
6:57 PM






